[Review] The meaning of life
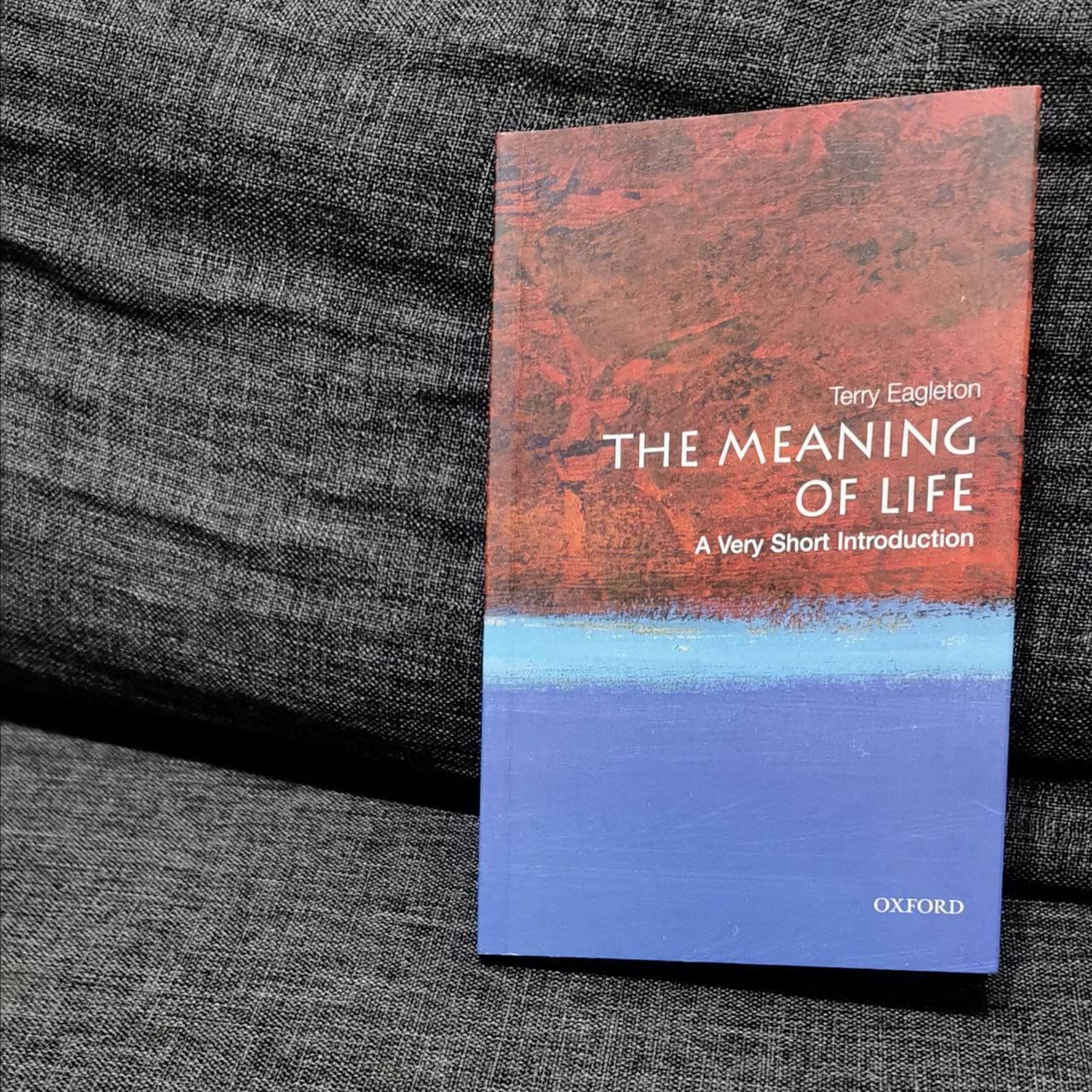
We may believe that our lives have value and meaning; but the truth is that we exist simply as the helpless instruments of the Will’s blind, futile self-reproduction.
Buku ini rasanya terlalu keren untuk dilewatkan dari dibuatkan ulasannya di blog yang sudah usang ini. Buku kecil nan imut ini adalah satu dari 427 buku dari seri The very short introduction dari Oxford. Ditulis oleh Terry Eagleton, seorang profesor literatur Bahasa Inggris, buku ini menawarkan pembahasan filosofis tentang arti sebuah kehidupan.
Secara garis besar, saya suka sekali dengan struktur buku ini. Terdiri dari 4 bab, bab pertama lebih banyak membahas tentang pertanyaan itu sendiri. Sebagai profesor literatur, penulis berhasil membawa kita untuk mendalami tentang kata “meaning” itu sendiri. Apakah itu berarti tujuan? Atau mungkin makna/arti? Atau malah maksud? Mendalami pertanyaan ini penting untuk memahami substansi tentang hal yang kita bicarakan. Bagi saya bab ini juga menarik karena kita jadi bisa belajar bagaimana membuat sebuah pertanyaan yang baik.
We tend to assume that discovering the meaning of life would naturally be a worthwhile thing to do, but what if this is a mistake?
Kemudian bab kedua mulai membahas tentang permasalahan dari pembahasan pertanyaan ini sendiri. Di bab ini, penulis banyak membahas pandangan filosofis Schopenhauer. Di sinilah penulis mulai menanam bibit-bibit yang akan mengantarkan kita pada krisis eksistensial.
There used to be a debate in literary criticism about whether the meaning of a poem is somehow already there in the work, waiting for the reader to come and pluck it out, or whether it is something that we, the readers, bring to the poem.
Selanjutnya, di bab ketiga kita dibawa lebih jauh untuk merenungkan makna kehidupan dari sudut pandang yang lebih menarik lagi. Salah satunya adalah tentang apakah makna adalah sesuatu yang memang terikat pada suatu objek atau sesuatu yang kita berikan untuk suatu objek.
You would not lament the fact that you were not born wearing a small woolly hat. Babies being born sporting small woolly hats is just not the kind of thing one should expect to happen.
Bab ini akan memperdalam rasa frustasi dan krisis eksistensi yang kita rasakan sejak bab kedua. Pada akhirnya, jika kita terlahir di dunia ini tanpa makna/tujuan yang tertanam dari awal, mengapa sekarang kita harus repot-repot mencarinya?
The news that there is no given meaning to life is both exhilarating and alarming. The individual self has now taken over God’s role as a supreme legislator; yet, like God, it seems to be legislating in a void.
Sampai ke bab terakhir, akhirnya kita seperti diberi angin segar setelah sebelumnya dibuat frustasi. Di bab ini penulis seakan ingin mengembalikan lagi pengarapan bagi para pembaca.
Though each performer contributes to ‘the greater good of the whole’, she does so not by some grim-lipped self-sacrifice but simply by expressing herself. There is self-realization, but only through a loss of self in the music as a whole.
Saya suka sekali analogi permainan jazz di bab terakhir. Di sini penulis menawarkan analogi bahwa bisa saja arti kehidupan itu bisa diibaratkan seperti penampilan jazz. Tiap pemain berkontribusi terhadap musik yang dihasilkan dengan melarutkan diri dalam permainannya. Artinya, arti kehidupan mungkin hanya bisa dinilai dari keseluruhan performa individual yang terlibat di dalamnya. Terlihat utopis, namun menurut saya ini salah satu alternatif menarik untuk memandang makna kehidupan.
Rather than serve some utilitarian purpose or earnest metaphysical end, it is a delight in itself. It needs no justification beyond its own existence. In this sense, the meaning of life is interestingly close to meaninglessness.
Pada akhirnya, menurut saya sangatlah alami bagi manusia sebagai mahluk yang punya kesadaran untuk merenungkan makna kehidupannya. Meskipun begitu, memikirkan pertanyaan ini rasanya seperti mencari pembenaran akan kehidupan kita, yang mana terkesan sia-sia. Toh, kita tak pernah meminta untuk dilahirkan di dunia ini. Jika perlu pembenaran, maka setidaknya bukan kita yang perlu melakukannya.
Through this enabling detachment, we would be better able to see things for what they are, as well as to relish them more fully.
Lagi pula pada akhirnya, makna atau arti kehidupan kita akan diinterpretasikan secara berbeda dari 3 sudut pandang, yaitu dari yang menciptakan kita (baik itu Tuhan, maupun orang tua kita), kita sendiri, dan dari sudut pandang orang lain. Kita bisa saja menentukan tujuan, makna, atau arti dari kehidupan kita masing-masing, namun itu hanya akan berlaku untuk diri kita sendiri. Pihak lain masih bebas menginterpretasikannya sesuai keinginan masing-masing. Itu pun kalau mereka punya waktu untuk memikirkannya.